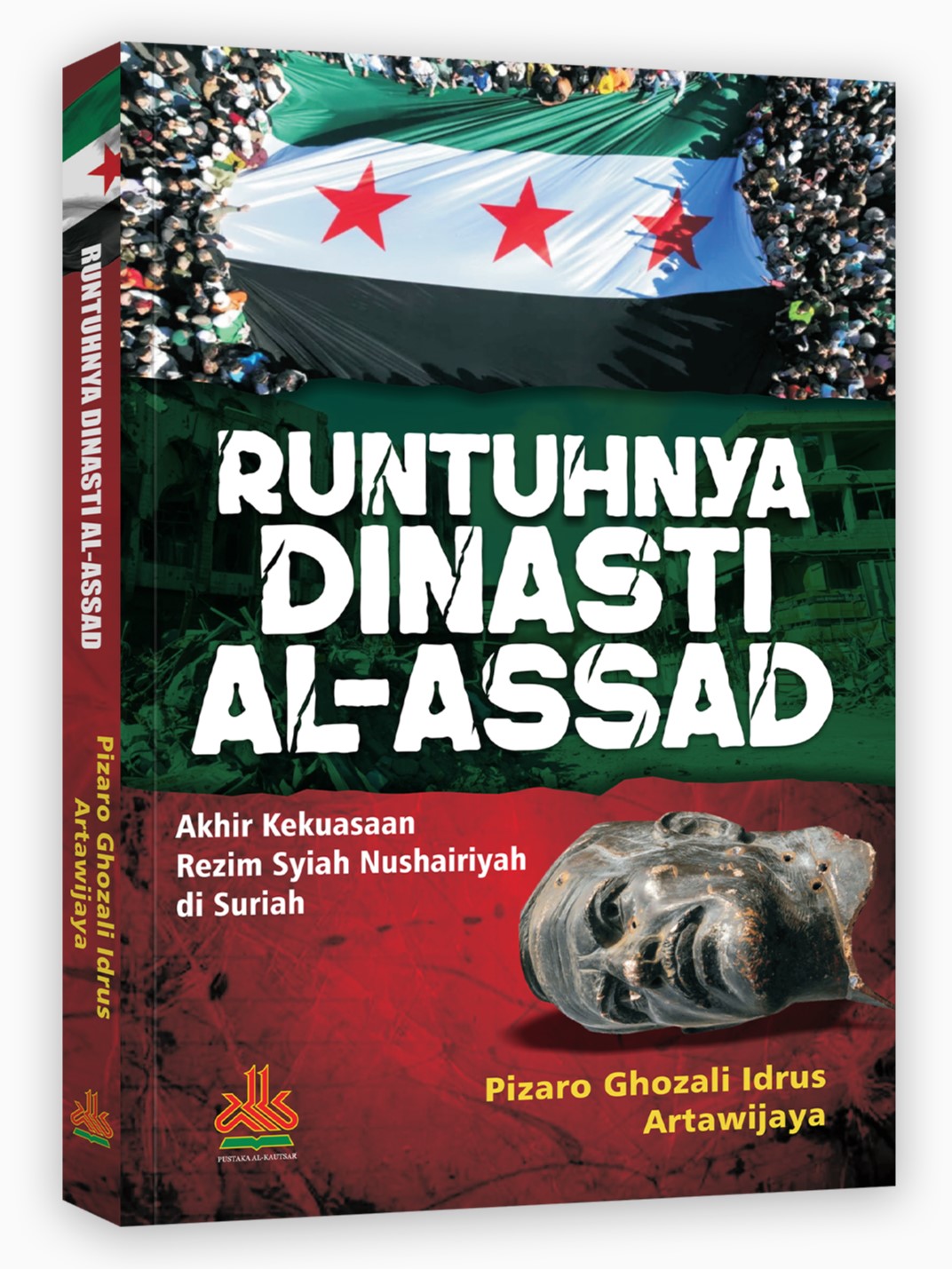Kamis lalu, dunia Gaza kembali diguncang oleh kabar kematian Yasser Abu Shabab. Insiden ini bukan sekadar masalah keamanan lokal. Ia sekaligus membuka kembali jurang besar antara narasi yang dibangun Israel tentang Gaza dan realitas kompleks di lapangan.
Selama ini, Abu Shabab digambarkan Israel sebagai “alternatif bagi Hamas,” sosok yang bisa memimpin Gaza pascaperang. Namun kenyataannya, dia adalah figur kontroversial, bahkan di wilayah tempat ia beroperasi. Dengan banyaknya kelompok bersenjata, suku, aliansi, dan urusan yang belum terselesaikan, Abu Shabab dikelilingi musuh.
Reaksi di media sosial segera setelah kabar kematiannya muncul menunjukkan betapa dia menjadi figur yang dicari banyak pihak. Semua orang cepat-cepat membangun narasi: menyalahkan, membela, atau membersihkan namanya. Satu hal jelas terlihat: tidak ada kekuatan yang cukup untuk melindungi orang yang bekerja sama dengan Israel.
Suku Abu Shabab sendiri, suku Tarabin, dengan cepat menyingkirkan dirinya. Dalam pernyataan resmi, mereka menyebut Abu Shabab sebagai “episode kelam” dan menegaskan kematiannya menutup “bab memalukan.” Suku itu juga berjanji tidak akan membiarkan anggota lain bergabung dengan milisi yang “melayani pendudukan.”
Langkah ini bukan sekadar upaya menjauhkan diri. Pernyataan tersebut juga menyampaikan pesan kepada seluruh warga Gaza: “Pria ini bukan bagian dari kami, jangan hubungkan urusan dengannya kepada kami.”
Penyebab langsung kematian Abu Shabab disebut buah bentrokan dengan anggota keluarga Abu Snima yang dikenal terlibat aktivitas kriminal. Sebuah perkelahian bersenjata pecah setelah Abu Shabab menolak membebaskan seorang anggota keluarga yang ditahannya, memicu perhitungan kekuatan lebih luas di wilayah itu. Dari sini terlihat jelas: Abu Shabab tidak membangun kepemimpinan, ia hanya terlibat perebutan kekuasaan.
Di sinilah peran Israel muncul. Selama bertahun-tahun, pihak pertahanan, media, dan politik Israel mencoba “menciptakan mitra” di Palestina—orang lokal yang tampak kuat, berpengaruh, tetapi bersedia mengikuti arahan Israel. Dari usaha itu lahirlah “bintang sementara” seperti Abu Shabab.
Abu Shabab memang memenuhi kriteria yang disukai Israel: bersenjata, mau bekerja sama, menentang Hamas, namun tidak berafiliasi dengan Otoritas Palestina, dan tampak bisa menjaga ketertiban. Namun kenyataannya, kekuasaannya hanya berlaku di wilayah yang masih dikendalikan Israel. Di luar itu, ia tidak punya legitimasi atau dukungan lokal.
Tipe pemimpin seperti ini bukan hal baru. Milisi Tentara Lebanon Selatan mengandalkan Israel selama dua dekade, namun hilang begitu saja ketika Israel menarik diri.
Siapa pun yang diberi kekuasaan dari luar tanpa basis dukungan lokal hanya hidup sebentar. Israel, sekali lagi, membangun ilusi tentang sosok yang dianggap bisa memimpin Gaza, bukan berdasarkan kebutuhan nyata rakyat Palestina.
Kematian Abu Shabab mengingatkan satu hal penting: kepemimpinan tidak bisa dipaksakan dari luar. Abu Shabab tampak sebagai orang kuat, tetapi sesungguhnya ia bergantung pada senjata, kekacauan, dan permainan ganda antara aktor lokal dan Israel. Gaza bukan tempat di mana pemimpin bisa dipaksakan dari atas. Sejarah dan dinamika masyarakatnya jauh lebih kuat daripada rekayasa apa pun.